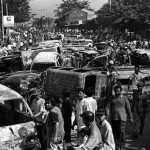Abdul Ghopur
Belakangan, fenomena berpikir merdeka nampaknya sedang menghinggapi dan menggejala dalam pikiran bangsa Indonesia. Fenomena ini merupakan akumulasi dari ketidakpuasan masyarakat terhadap situasi kebangsaan yang ada. Muncul di kalangan sebagian besar masyarakat terutama orang-orang muda sebuah pertanyaan kritis, masih berfungsikah imaji kolektif kita sebagai bangsa? Pertanyaan ini mengemuka karena bertubi-tubi prestasi buruk kita dapatkan di dunia, pemenang lomba korupsi, bangsa penghasil teroris, lamban dalam penanganan bencana alam dan negara tidak aman untuk investasi. Ditambah pemutusan hubungan kerja (PHK) dimana-mana yang mengakibatkan makin panjangnya deret/angka pengangguran. Dengan sederet prestasi terburuk tersebut, layakkah kita berbangga menjadi bangsa Indonesia? Tentu saja jawabannya sangat tergantung dari “posisi apa” yang sedang kita jalani. Jika posisi kita adalah TKI atau pengangguran, maka jelas, Indonesia tidaklah berarti apa-apa. Sebaliknya, jika posisi kita adalah koruptor, teroris dan pejabat pemerintah (yang korup), maka jelas, Indonesia adalah negeri sorga.
Sesungguhnya kita tahu bahwa nalar, ego dan semangat keindonesiaan bukanlah sebuah warisan yang ditemukan atau pun datang tiba-tiba. Tidak pula merupakan kesadaran suci dan primordial. Dalam bahasa Edward Said (1994), sejarah manusia Indonesia adalah konstruksi ideologis yang didasarkan pada satu kombinasi yang ganjil antara “yang empiris” dan “yang imajinatif.” Yang empiris berupa manusia dan tanah, sedang yang imajinatif adalah pikiran dan cita-cita bersama. Nalar-rasa-karya sebagai bangsa Indonesia dengan demikian adalah hasil dari pergulatan emosional, intelektual dan ideologis yang diciptakan, dibangun, dan diperjuangkan bersama-sama bertahun-tahun. Sebab, sebelum tereja sebagai Indonesia, masyarakat Nusantara lahir dan tumbuh dalam komunitas lokal yang masing-masing memiliki identitas, tradisi, bahasa, ruh dan pemimpin yang berasal dari kalangan mereka sendiri. Mereka telah menyejarah sebagai produk budaya yang terkait dengan sistem kekuasaan yang bersifat eksternal maupun internal yang melalui “imaji” dan “empirisnya” berbicara dunia di sekitarnya (M. Yudhie Haryono, 2009). Baru setelah kemerdekaan maka daerah tadi dilabeli nama baru dengan tulisan “propinsi/kabupaten” dan diberi “jiwa dan ruh” baru yang bernama “jiwa-ruh keindonesiaan.” Persoalannya, apakah kehadiran jiwa-ruh keindonesiaan itu mengganti jiwa-ruh kedaerahan menjadi kenasionalan (from tribal to nation), apakah terjadi “perkawinan” atau “pelenyapan,” terjadi “pertikaian” yang tak kunjung selesai atau justru roman perkawanan yang harmonis?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi penting sebab, salah satu fungsi dari kebangsaan Indonesia adalah untuk membantu kita membangun makna tentang diri; untuk menjelaskan dari mana kita berasal dan mengapa tradisi-tradisi kita istimewa dan khas. Sedang secara politik, sejarah kemerdekaan pada tangal 17 Agustus 1945 merupakan administrasi “akad nikah.” Satu perjanjian “suci” antar–berbagai gugus menuju persatuan-kesatuan menjadi keluarga besar Indonesia. Dus, peristiwa itu adalah kontrak sosial dalam teori politik modern, dan kontrak historical bloc dalam teori perjuangan antara sosok bernama “negara republik” dengan sosok “putri daerah.”
Pernikahan agung antara republik dan putri daerah menjadi jembatan emas dan pintu gerbang menuju “cita-cita kolektif” antar–berbagai gugus yang berbeda. Terciptalah cita-cita subtansi sebagaimana tercantum dalam mukadimah UUD 45’, melindungi segenap rakyat dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Karena alasan persamaan nasib sepenanggungan tersebut maka, harta, harapan, cita-cita dan sumber daya yang dimiliki daerah telah diberikan sepenuhnya pada Republik Indonesia. Namun sangat disayangkan, kecintaan dan kesetiaan “putri daerah” tidak memperoleh balasan yang sepadan dari “sosok negara.” Sebaliknya, yang terjadi adalah tindakan semena-mena. Kesehatannya tidak diperhatikan, jiwanya disakiti, kekayaan alamnya dikuras, pendidikan diterlantarkan, pendeknya nafkah lahir dan batin tidak dipenuhi sebagaimana yang diharapkan. Akibatnya, sumpah setia dan kecintaan “putri daerah” pada sosok “negara bangsa” melemah, sakit hati, dan bahkan sebagian melawan dan minta cerai. Negara menjadi uncivil state dan disfungsi bahkan menajam jadi destroyer yang kejam pada pasangan hidupnya.
Lalu timbul pertanyaan, mengapa beragam suku, agama dan etnis yang sedemikian beragam dan tempat tinggal yang terpencar di berbagai pulau rela dan sepakat melebur diri dalam rumahtangga bernama bangsa dan negara Indonesia? Sedikitnya ada dua jawaban. Pertama, adanya agama dan ideologi yang dianut rakyat. Agama dan ideologi inilah yang menjelaskan pentingnya upaya mentransendenkan ego demi rasa yang lebih “agung.” Agama dan ideologi menjelaskan adanya “ego-rasa” kepemilikan sekaligus kejuangan mahkluk hidup untuk memperoleh kemerdekaan, keadilan, keamanan, kebebasan dan kesejahteraan. Satu imaji yang dapat digapai dengan cara berbagi dalam bhinneka tunggal ika dan subsidi silang.
Kedua, adanya stimulasi dari luar berupa penjajahan (imperialisme). Musuh luar ini telah berperan menjadi kekuatan pendorong bagi menguatnya rasa senasib–sependeritaan, sehingga melahirkan sebuah solidaritas untuk melawan (fight against) kekuatan asing yang pada urutannya mengantarkan lahirnya sebuah identitas bangsa bernama Indonesia.
Indonesia dengan demikian adalah sebuah lokus yang di dalamnya terdapat kekayaan nalar, ego, tradisi, sistim nilai, cita-cita luhur kemanusiaan, moralitas keagamaan, dan naluri sosial untuk membentuk sebuah negara bangsa yang di dalamnya kita semua bisa tumbuh dan tinggal secara nyaman dan beradab. Pertumbuhan inilah yang secara sosial-antropologis kita sepakati sebagai “kontrak sosial” dan “komitmen politik” untuk bersama-sama membangun, memiliki dan menjaga “rumah Indonesia” agar gagah, martabatif serta menjadi subyek yang ikut serta menjaga ketertiban dunia.
Persoalannya kemudian mengapa prinsip-prinsip kebangsaan, kenegaraan serta kewarganegaraan semakin hari semakin jauh? Bahkan jauh lebih menjauh setelah dikobarkannya reformasi Mei 98’? Ada banyak jawaban, tetapi yang terpenting adalah karena pertama, problem Indonesia sesungguhnya adalah keberlangsungan manajemen negara paska kolonial yang tak mampu menegakkan kedaulatan hukum, memberikan keamanan dan keadilan bagi warganya. Di dalam ketiadaan keadilan, keamanan dan perlindungan hukum bagi individu untuk mengembangkan dirinya, orang lebih nyaman berlindung di balik warga-tribus (tribalisme, premanisme, koncoisme dan sektarianisme) ketimbang warga-negara. Persoalan ekonomi-politik yang bersumber dari manajemen negara yang korup menyisakan kelangkaan dan ketimpangan alokasi sumberdaya di rumah tangga kebangsaan.
Jika para politisi dan aparatur negara hanya sibuk mengamankan kekuasaan dan dapurnya sendiri, maka individu akan segera berpaling ke sumber-sumber tribus sebagai upaya menemukan rasa aman. Di sinilah tak jarang persoalan ekonomi-politik yang objektif disublimasikan ke dalam bentrokan identitias yang subjektif. Bahkan belakangan muncul pula gerakan “perlawanan sipil” serentak dari masyarakat dengan mengibarkan bendera bajak laut berlogo tengkorak topi jerami dengan tulang manusia bersilang, di banyak daerah Indonesia. Meski masih mengibarkan Sangsaka Merah Putih di atas bendera bajak laut film anime Jepang itu, sebagai rasa nasionalisme dan masih adanya “sisa” cinta untuk Indonesia. Hal ini sesungguhnya protes serta “kritik cinta” masyarakat terhadap kesewenang-wenangan penguasa yang dianggap sudah lupa diri dan tak peduli nasib rakyat Indonesia. Di samping perwujudan dan peluapan rasa merdeka serta tak ingin dikekang dengan kebijakan-kebijakan yang dianggap menyengasarakan dan tak sesuai dengan prikemanusian dan prikeadilan, singkatnya tak sesuai dangan pembukaan undang-undang dasar 1945 dan cita-cita proklamasi 45’. Apalagi janji-janji manis kampanye saat Pilplres 2024.
Kedua, kita belum siap menerima keragaman. Padahal, keragaman bangsa bisa menjadi kekayaan jika negara mampu menjalankan fungsinya sebagai, apa yang disebut Mohammad Hatta, ‘panitia kesejahteraan rakyat.’ Padahal bangsa Indonesia sesungguhnya adalah ‘konsepsi kultural’ tentang suatu komunitas yang diimajinasikan sebagai entitas dari warisan sejarah dan teritoral kerajaan. Artinya, dulunya kita berasal dari asal dan lokus yang berbeda-beda, namun kini menyatu menjadi komunitas bangsa. Sedang negara Indonesia adalah ‘konsepsi politik’ tentang sebuah entitas yang tumbuh berdasarkan kesadaran politik untuk merdeka dengan meletakkan individu ke dalam kerangka kerakyatan. Dalam kerangka ini, setiap rakyat dipertautkan dengan suatu komunitas politik dalam kedudukan yang sederajat di depan hukum, dengan operasi atas prinsip kekariban dan keadilan. Artinya, kita semua sama di mata hukum dan layak sejahtera seperti yang dirasakan oleh para elit.
Secara politik, sepertinya negara kita sedang mengalami kegagalan (state manqué) merealisasikan pesan dasar dalam muqadimah UUD 45’. Ada dua alasan kegagalan yang dapat kita kemukakan. Pertama, gerakan reformasi masih menyisakan tradisi mitos state, yakni skripturalisme. Hidup dalam skripturalisme artinya para aparatus negara kita hanya mengandalkan “catatan laporan” tanpa inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan. Padahal, catatan laporan para bawahan seringkali dibuat “asal bapak senang” (ABS). Dus, hidup dalam fase skripturalisme pada akhirnya menyerahkan akal pada laporan, menitipkan masa depan pada masa lalu, lebih mempercayai “antek” daripada intelek, menggantungkan keselamatan pada “benda mati,” dan merasa sempurna dalam perasaan tanpa tahu apakah sesungguhnya yang harus dilakukan agar sampai pada cita-cita dan idealitas kemanusiaan.
Kedua, gerakan reformasi baru mempraktekkan materialism state. Karakter dasar dari negara material adalah “meminta rakyat banyak berkorban” yang diimbangi dengan gaya hidup “high class” para aparatus negara. Kenaikan gaji legislatif dan eksekutif yang sangat mencolok disertai “banyaknya orang mati antri dapat Bansos” adalah buktinya. Pada fase negara material ini yang dikembangkan baru gagasan individualisme, unitarian, simbolik dan profanitas. Yang sakral, kerumunan dan abstrak memang telah berkurang dan diganti dengan hal-hal baru yang lebih efisien-subtansial. Problemnya, fase negara material ini tidak dibarengi dengan pembangunan karakter dan etos kerja (terutama etos kerja para aparatusnya). Padahal pembangunan karakter (character building) adalah prasyarat bagi pembangunan negara secara menyeluruh (nation-state building). Itu artinya, tanpa karakter yang kuat niscaya etos kerja dan martabat negara tidak akan “hadir” di keseharian kita. Ketika etos kerja melemah maka sinetron kita diisi dengan cerita setan dan episode “lawakan” serta ucapan Tuhan yang diulang-ulang, ritual ibadah yang berlebihan. Ketika kerja tidak dibudayakan maka korupsi menjadi jawaban.
Secara formal-politis memang Indonesia baru terlahir pada 17 Agustus 1945. Namun menafikkan proses panjang sebelum itu berarti kita berpikir ahistoris dan secara moral menyakiti para pejuang yang telah berjasa bagi lahirnya republik ini. Dengan moral sejarah pula kita mengharapkan adanya “pemuliaan manusia merdeka” yang selalu berjuang menuntut Indonesia menjadi seperti yang diharapkan bersama dan bukan pembunuhan dan penghilangan paksa oleh aparatus negara sebagaimana telah dipraktikkan oleh orde sebelumnya.
Sebaliknya, evaluasi, kritik dan revolusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah suatu kewajaran dan keharusan sejarah. Di sinilah pentingnya para pemimpin harus memberikan teladan dan pembelajaran agar rakyat dan bangsanya bangkit ketika terjadi keterpurukan dan di tengah ketidakberdayaan rakyat, baik karena ekonomi maupun bencana alam, untuk tegak kembali dengan mencanangkan loncatan prestasi menuju Indonesia emas yang selalu digaungkan pemerintah. Supaya rakyat merasakan substansi rasa kebanggaan atas kebangsaannya dari bagian dan pemilik sah dari suatu bangsa, agar mereka tak kehilangan sense of belongingnya. Imaji dan materialisasi Indonesia ke depan adalah menjadi negara modern yang bebas merdeka. Yaitu sebuah negara yang berfungsi aktif menjamin kebebasan tiap-tiap warga negara untuk mengaktualisasikan hak-hak ekonomi, hak-hak politik, dan hak-hak sipil dalam kepastian equal opportunity. Di sini hukum sebagai aturan main sudah seharusnya ditegakkan oleh negara secara adil.
Dus, Indonesia harus menjadi law geverned state yang diisi oleh manusia-manusia Indonesia merdeka. Sebab, tak ada penjajahan paling dahsyat di muka bumi, selain penjajahan pikiran. Maka berpikir dan jadilah manusia merdeka. Sebab hanya dengan menjadi manusia Indonesia merdekalah kita dapat bebas berkehendak berbuat sesuai hati nurani untuk kemajuan rakyat dan bangsa yang hakiki. Bukan malah panik dengan munculnya “hantu” bendera bajak laut yang hanya simbol “perlawanan” terhadap penindasan dari sebuah film fiksi anime Jepang![]
Penulis adalah Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Bangsa,
Inisiator Kedai Ide Pancasila; Pendiri Indonesia Young Leaders Forum.